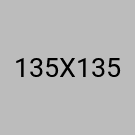Santri Akhir Jaman dan Sebuah Pemakluman
Santri Akhir Zaman dan Sebuah Pemakluman
Menjadi santri merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi sebagian orang. Sebagaimana seorang siswa yang bangga dengan sekolahannya. Jika setiap siswa yang mempunyai karakter dan minat yang beragam, santri pun juga demikian.
Berbicara tentang santri, ada suatu pola yang sama dialami santri. Sebuah pola yang diciptakan melalui nafas zaman yang membentuk gaya hidup santri. Tentu santri pada zaman pergerakan berbeda dengan santri akhir zaman.
Santri tempo dulu, untuk menjadi seorang alim merupakan hal yang membutuhkan usaha yang sangat keras. Bagaimana tidak? Pada waktu itu, akeses kitab merupakan hal yang sangat sulit. Belum lagi masalah bertahan hidup di pondok. Kiriman tak menentu. Segala hal memang benar-benar sulit dan menyulitkan. Santri harus kreatif dan cakap agar bisa survive untuk sesuap nasi atau sebuah kitab baru.
Almaghfur lahu simbah kyai Abdul Karim sewaktu nyantri di Bangkalan rela berjalan kaki dari Magelang menuju Bangkalan karena uang untuk perjalanan beliau gunakan untuk membeli kitab baru.
Kitab Jurumiyah milik Almaghfur lahu simbah kyai Marzuqi Dahlan yang aus sampai-sampai kitab tersebut sulit dibaca karena terlalu sering dimuthola’ah. Begitu juga dengan Almaghfur lahu simbah kyai Mahrus Aly, dalam belajar beliau seringkali bernadzar (tidak memakan buah ini sebelum memahami kitab ini, misalnya), sebagai ikhtiar mencapai capaian yang memuaskan dalam belajar.
Belum lagi sewaktu mengaji, santri pada zaman dulu harus tetap mawas diri karena situasi Negara yang masih belum stabil. Kesulitan belajar merupakan hal yang nyata dan kompleks. Itu dulu, lain halnya sekarang.
Sekarang belajar menjadi begitu mudah. Fasilitas dan program pondok selalu memudahkan santri untuk tetap bisa belajar dan berkembang. Kitab-kitab yang dulu sulit diakses, sekarang bisa. Bahkan tak jarang sudah tersedia yang pethukan dan terjemahan. Namun demikian, terhadap teori, seseorang menghadapi abstraksi yang –betapa pun itu dirumuskan dari kenyataan– membutuhkan kemampuan menembus kerumitan bahasa agar bisa membumikannya melalui tubuh untuk berbuat sesuatu. Berbeda dengan tindakan (teladan dari cerita-cerita pendahulu), seseorang dapat langsung mengukur kemungkinan dan ketidakmungkinan untuk dipraktikkannya sendiri tanpa harus mumet memahami maksudnya.
Tindakan sendiri nyaris selalu tentang sesuatu yang telah terjadi, sudah dilakukan –pendeknya: berlangsung pada masa yang sudah lewat. Entah itu lima menit yang lalu atau seribu tahun silam.
Maka lebih mudah memanggil masa lalu ketimbang menarik masa depan tiap kali hari ini dirasa buruk, suram, atau pun membosankan. Pada masa lalu itu, orang dapat menarik tindakan-tindakan yang dianggap hebat, penting, menentukan dan sudah terbukti. Sedangkan pada masa depan, orang hanya bisa mereka-reka, meraba-raba, sebab ia masih bersifat teori, masih berbentuk abstraksi.
Ketika seseorang lebih memilih berpaling pada masa lalu, karena masa kini yang tidak enak dan tidak memuaskan, ia sesungguhnya sedang merindukan sesuatu yang hilang, hal ihwal yang ada pada masa lalu tapi raib pada masa kini.
Perlu tindakan untuk menghadirkan kerinduan yang didambakan itu. Sayang sekali, jalan untuk menghadirkannya sulit dan tidak menyenangkan, sama sulitya dengan belajar dari teori dan abstraksi yang ada pada kitab.
Terhadap teladan yang talah dicontohkan oleh santri zaman dulu, dengan tawadlu’nya kita seringkali mengatakan tidak mampu. Tidak punya kema(mpa)uan untuk itu.
Dan setelah itu, kita menjadi lebih suka bercerita dan mendengarkannya dibanding belajar teori-teori. Mengenai hal ini, dalam satu kesempatan pengajian tafsir Jalalain, Romo Kyai Ahmad Mahin Thoha dengan dawuh, “santri isih enom ki sing penting ngaji kitab sing mbahas qaidah karo ushul, ora cerito, moco kitab cerito suk nak wes tua wae.”
Jika memang demikian, kita—santri akhir zaman hanya membesarkan masa lalu, sekedar membanggkan apa yang telah dilalui dan dicapai oleh guru-guru kita, pendahulu kita. Sebatas menghidupkan tindakan dan sikap beliau semua hanya dalam cerita dan kenangan yang selalu diperdengarkan untuk membunuh kebosanan dalam kelas.
Ya memang karena belajar itu sulit, belum lagi takziran karena tidak hafal atau terlambat datang. Hal itu menjadikan segala hal –seolah— semakin menyulitkan dan tidak mengenakkan. Ini semua mungkin karena terlalu lama belajar dengan (tidak) berfikir.
Menjadi santri akhir zaman begitu membanggakan, bahkan setiap tahun selalu dirayakan. Tapi harap maklum, kesulitan dahulu dan sekarang memang berbeda, juga tantangannya. Tapi apapun itu, kabar baiknya Gusti Allah selalu Maha Penyayang. Senjata ampuh santri akhir zaman adalah prasangka baik kepada-Nya. Juga pada hamba kinasihnya. Idz bi dzikiri him tuftahu abwabu al-samawaati al-aliyah. Lantaran itu, semoga mendapat futuh. []
Oleh: Muhammad Fahda (Bag: B.04)